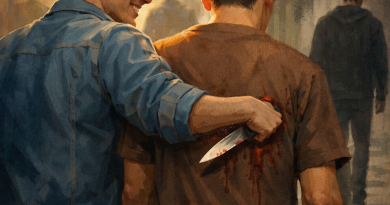Kiyai Pejuang Jadi Pahlawan Nasional ” Layakah?
Oleh:Mohammad Fathi Royyani
Gelar pahlawan merupakan Pengakuan negara bagi kiprah dan perjuangan satu tokoh terhadap upaya-upaya kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk mendapatkan pengakuan dari negara dibutuhkan banyak persyaratan, baik yang sifatnya administratif maupun bukti-bukti otentik keterlibatan tokoh tersebut dalam usaha kemerdekaan. Adanya berbagai persyaratan tersebut yang membuat satu tokoh, walaupun berdasarkan cerita lisan di masyarakat sangat berjasa dalam usaha kemerdekaan, tidak serta merta mendapatkan gelar pahlawan.
Persoalannya, nalar para pakar yang duduk di Dewan Gelar masih menggunakan atau menganut cara berpikir ilmu sejarah lama yang memiliki adagium “Tanpa ada dokumen, tidak ada sejarah”. Sejarah yang demikian pertama kali dicetuskan oleh Robert H Lowie yang menolak penggunaan tradisi lisan sebagai sumber sejarah. Robert H Lowie dan pendukungnya menganggap bahwa dokumen yang direkam melalui tradisi lisan adalah cara-cara primitif yang tidak tidak historis. Tegasnya, sejarah adalah yang tertulis.
Pendapat ini tentu mengalami banyak penolakan, diantaranya Jan Vansina yang bahkan meletakkan tradisi lisan sebagai sejarah itu sendiri. Pendapatnya ini bahkan melampaui kalangan yang masih melihat tradisi lisan sebagai sumber sejarah yang kredibel. Menurut Jan Vansina, testimoni yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun temurun dalam ruang memori dan ingatan masyarakat pendukungnya merangkum perjalanan sejarah masyarakat dari waktu ke waktu tanpa terikat oleh ada atau tidak adanya tradisi tulis. Tradisi lisan tidak saja sumber sejarah melainkan sejarah perkembangan masyarakat itu sendiri. Selain itu, dengan menggunakan tradisi lisan, sejarah yang disajikan akan memiliki sentuhan rasa “kemanusiaan” tidak sekaku dokumen yang tertulis.
Tradisi lisan adalah cerita yang beredar di masyarakat dalam terus dipelihara dalam rentang waktu yang lama, Asosiasi Tradisi Lisan pada tahun 2015 menerbitkan satu buku yang berjudul Metodologi Kajian Tradisi Lisan yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Buku ini mengulas cara menggali dan menganalisa data bersumber dari tradisi lisan yang ada di masyarakat. Artinya, tradisi lisan bukan lah cerita yang meng-ada-ada atau dongen, tradisi lisan perlu dilihat sebagai rekaman peristiwa yang diturunkan bergenerasi, seperti kisah-kisah heroik para kiai dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia lebih banyak terekam dalam dokumen yang berbentuk tradisi lisan.
Dengan hadirnya tradisi lisan, kalangan-kalangan yang selama ini “terpinggirkan’ secara penuturan sejarah yang mendasarkan pada dokumen, mendapatkan ruang ekspresinya. Termasuk dalam hal ini adalah para kiai dan kalangan pesantren yang menurut tradisi lisan yang berkembang di masyarakat sangat berperan dalam berbagai perjuangan kemerdekaan. Tidak itu saja, bukti-bukti akademis, seperti kajian literature yang menyebutkan berperan besarnya suatu lembaga dalam membentuk masyarakat yang agamis, egaliter, dan bersedia berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia kurang juga mendapatkan perhatian dalam mendukung pengakuan negara terhadap kepahlawanan seseorang.
Kalangan Kiai dan peran pesantren misalnya, walaupun sudah banyak kajian, baik dari sarjana asing maupun sarjana dalam negeri, yang meneliti kiprah suatu kiai di pesantren, baik dalam membentuk masyarakat yang tidak saja mengerti mengenai agama melainkan juga rela berjuang untuk kemerdekaan tetapi tidak cukup bukti bagi kiai di pesantren mendapatkan gelar kepahlawanan nasional.
Kareel Steenbrink misalnya, banyak melakukan penelitian dan penulis mengenai kondisi umat Islam pada awal abad ke-20, yang di dalamnyya menyebut peran pesantren dan kiai dalam membentuk masyarakat yang terdidik. Artinya melalui kiprah kiai dan pesantren, masyarakat menjadi tercerahkan dan siap mengehadapai perubahan zaman.
Di bawah asuhan Karel Streenbrink terdapat banyak cendekiawan muslim, seperti Husnul Aqil Suminto yang menulis disertasi mengenai Politik Islam Hindia Belanda. Karya
- Penulis Adalah Ktivis NU
- dan Peneliti Di BRIN